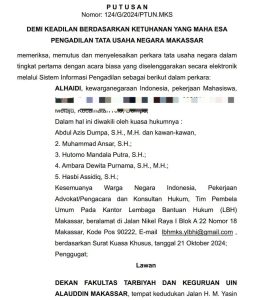Oleh : Anugrah Ramadhan
Seperti biasa, pagiku belakangan ini kadang kuhabiskan di sebuah kantor stasiun televisi swasta, yah kebetulan saya sedang menjalani magang di sana, secangkir kopi hitam dengan setengah sendok gula tak lupa ku buat, sebelum akhirnya saya duduk dan mengambil koran langganan kantor, yang sedari subuh menanti tuk dibaca. Itu juga kalau belum ada tugas liputan dari mentor.
Sama dengan anak laki-laki lainnya, rubrik sepak bola selalu menjadi idaman. Namun beberapa minggu terakhir ini, halaman bertajuk internasional di setiap koran yang memberitakan tentang kerusuhan di Prancis, perlahan mulai menarik perhatianku. Hal itu mengingatkanku dengan revolusi Bastille yang disajikan di buku PKN ketika masih duduk di bangku SMP dulu.
Begitupun yang terjadi di media sosial milikku, hampir semuanya dihiasi video dan foto kekerasan aparat kepolisian terhadap demonstran yang belakangan dikenal dengan sebutan Gilets Jaunes/Yellow Demonstrant atau gerakan “rompi kuning,” yah mereka para pengunjuk rasa memang menggunakan sebuah rompi berwarna kuning menyala saat menjalankan aksisnya, namun apa yang sebenarnya dituntut oleh gerakan ini?
Peristiwa anarkis yang berlangsung sudah lebih dari sebulan tersebut, awalnya dimulai saat warga kota Paris menuntut Presiden Prancis Emmanuel Macron agar membatalkan kebijakannya terkait kenaikan harga BBM.
Beberapa sumber menyebut jika awalnya para demonstran dan pemerintah cukup kooperatif dalam menghadapi isu ini, hal itu terbukti dengan berlangsungnya keterbukaan antar kedua pihak. Dari sana, Macron kemudian mangambil langkah konsensi dengan mengabulkan tuntutan demonstran, hal itu dipilihnya agar kondisi negara bisa kembali pulih akibat ketidakstabilan perekonomian pasca kerusuhan pertama.
Perwakian dari kelompok gerakan rompi kuning pun juga mengimbau agar massa aksi menahan diri untuk tidak turun ke jalan. Tetapi selang beberapa hari, tanpa alasan yang jelas, tuntutan massa kemudian berlanjut dan menyerang aspek kebijakan lainnya di pemerintahan yang belum lama berkuasa itu.
Pengaruh Oposisi
Saya mengindikasi, jika aksi anarkisme dan vandalisme yang berlangsung sejak 17 November lalu itu, menjadi panggung istimewa bagi pihak oposisi pemerintah dalam menunjukkan eksistensinya. Jika merunut pada sikap politis yang ada, hal itu sangat jelas menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah dalang dari peristiwa ini, meskipun beberapa media internasional tidak begitu menyoroti kekuatan oposisi yang menyelinap di antara barisan pengunjuk rasa.
Sebuah hal wajar, ketika kebijakan pemerintah dalam suatu negara yang menyusahkan warganya, terutama masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah, itu kemudian mendapat respon yang keras. Tetapi Macron sudah mengabulkan tuntutan tersebut, lalu apalagi yang diminta oleh gerakan rompi kuning ini? Mengapa semuanya mulai merembes ke arah yang lain, seperti kebijakan kenaikan upah, penurunan pajak, reformasi pendidikan dan ketenagakerjaan hingga berujung pada tuntuntan menurunkan Macron dari jabatannya, padahal ia barusaja dilantik tahun ini. Sangat janggal bukan?
Hal di atas, sehemat saya bukan sekedar tuntutan sebuah kelompok demonstran, namun lebih mengarah kepada kekuatan oposisi untuk menjatuhkan pemerintahan presiden yang sah. Karena pengunjuk rasa tidak akan mungkin melangkah sampai sejauh ini. Seperti yang disebut oleh Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castener yang menganggap gelombang unjuk rasa tersebut seperti menciptakan monster yang lepas dari penciptanya.
Dari pernyataan itu sudah barang pasti Christophe Castener menyinggung tangan dingin pihak oposisi yang memanfaatkan gerakan rompi kuning sebagai kuda perang dalam merusak citra Macron di mata masyarakat Prancis dan internasional.
Tokoh oposisi pun tidak tanggung-tanggung untuk muncul di publik dan secara terbuka mengajak masyarakat Prancis untuk turun ke jalan. Siapa lagi jika bukan rival Macron saat Pilpres kemarin, yakni Jean-Luc Malenchon dari partai La france Insoumise dan dibantu oleh pemimpin sayap kanan Prancis, Marine Le Pen yang tidak sejalan dengan sikap politis pemerintahan berkuasa saat ini.
Di tengah-tengah itu, aksi massa gerakan rompi kuning juga sebagian besar didominasi oleh warga yang tinggal jauh dari titik-titik kota unjuk rasa, sebut saja Paris, Marseille, Monaco dan St.Tienne. Usia mereka rata-rata berumur 17 hingga 40 tahun, para pelajar dan mahasiswa terlibat dan sebanyak 280 sekolah di Ibu Kota Prancis terindikasi menuntut tumbangnya pemerintahan Macron.
Ada banyak korban yang berjatuhan dari massa rompi kuning, deretan toko rusak parah, puluhan mobil yang hangus terbakar masih terparkir di jalanan, alun-alun beberapa kota tampak mencekam dan mendapat penjagan ketat dari personil kepolisian saat malam tiba, Macron pun sempat menaikkan status negara ke tahap darurat siaga, mengingat peristiwa ini belum menemui jalan keluar.
Indikasi Kudeta
Namun apakah benar kita bisa sepenuhnya menyalahkan oposisi di balik peristiwa ini? Seorang wartawan yang bertugas di Paris, Lucy Williamson menyebut tujuan utama demonstrasi itu adalah frustasi atas ekonomi dan ketidakpercayaan politik dari keluarga-keluarga miskin yang masih memiliki dukungan luas. Tetapi meskipun begitu, tuntutan masyarakat terkait BBM kemudian dieksploitasi oleh elit politik oposisi pemerintah, untuk kemudian dijadikan momentum dalam merusak kepercayaan publik terhadap rezim berkuasa.
Banyak masyarakat internasional yang bersimpati kepada gerakan rompi kuning ini, apalagi ketika melihat aparat keamanan melakukan tindak kekerasan terhadap peserta aksi. Demikian halnya dengan saya pribadi ketika baru mengikuti perkembangan beritanya. Namun faktanya tidaklah demikian, mengapa aparat kasar di jalanan dan Macron tetap menahan diri, hal itu didasarkan karena rezim berkuasa tidak lagi memiliki opsi konsensi bagi masyarakatnya, jika tuntutan massa semuanya dikabulkan maka akan berdampak pada kebijakan monoter yang kedepannya akan lebih menyulitkan pemerintah dan semua itu dilakukan demi kestabilan negeri dengan semboyan Viva La France tersebut.
Hal itu membuat Macron seperti “maju kena, mundur kena” tak banyak opsi yang bisa dibuat, dan imbasnya, rezim mau tidak mau harus menggunakan tangan besi dalam mengontrol gelombang kerusuhan. Praktis ini jelas menunjukkan kalau gerakan rompi kuning sebenarnya adalah gerakan murni yang kemudian hari dikendalikan oleh elit oposisi sebagai tameng dalam menyalurkan sikap politiknya.
Kerusuhan ini mengingatkanku akan Turki beberapa tahun lalu. Ketika itu Presiden Recep Tayyib Erdogan mulai memasuki masa akhir jabatannya dan akan bertarung kembali dalam pemilihan yang demokratis, namun dalam momen tersebut Turki mengalami keamanan yang terbilang darurat. Banyak aksi bom mobil dan peledakan di jalan-jalan Kota Istanbul yang memakan korban jiwa tidak sedikit, akhir dramanya berujung pada upaya kudeta pihak oposisi melalui serangan militer, meskipun hannya bertahan tidak lama.
Namun bedanya Turki dan Prancis, terletak pada sikap oposisi, jika yang terjadi di Turki dilakukan dengan kekuatan agresi, maka oposisi Prancis justru dilakukan dengan massif dan mejadikan masyarakat sipil sebagai pion terdepan.
Bagaimanapun indikasi itu masih terlalu dini untuk dikemukakan, tetapi masyarakat internasional harus objektif melihat isu ini dari segala aspek, bahwa elit oposisi adalah kelompok yang paling bertanggung jawab dalam nestapa berkepanjangan ini.
*Penulis merupakan mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi semester VII