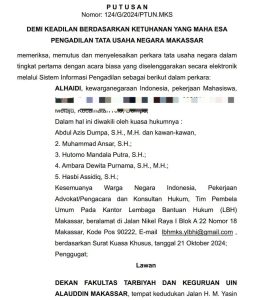Washilah – Gender menjadi tanda tanya di suku Bugis, karena ada yang mengidentifikasi dirinya bukan laki-laki maupun perempuan.
Peneliti Badan Riset Nasional dan Pegiat Kebudayaan, Dr Samsurijal Ad’han mengatakan, identitas gender adalah perasaan atau kesadaran yang berasal dalam diri untuk mendefinisikan seseorang sebagai perempuan, laki-laki, transgender, bigender, dan non biner.
Rijal juga menjelaskan, jika seseorang yang mengatakan dirinya sebagai non biner, artinya dia tidak mengidentifikasi dirinya di antara laki-laki dan perempuan.
“Secara biologis dan fisik mungkin dia laki-laki tapi dia merasa karakter dan perasaanya adalah perempuan maka ini disebut transgender,” ucapnya saat membawakan materi di seminar kebuayaan bertajuk “Seksualitas dan Gender di Kebudayaan Bugis Makassar” oleh Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin yang bekerja sama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PWNU Sulawesi Selatan, Senin (12/09/22).
Sementara Seksualitas, kata Rijal merupakan sesuatu yang bersifat alami dan bukan konstruksi sosial budaya. Masyarakat bugis mengenal dua jenis seksualitas, yakni uruwane (laki-laki) dan makkunrai (perempuan).
“Seksualitas merujuk pada ketertarikan secara seksual baik secara romantis maupun emosional pada individu lain yang memiliki jenis kelamin dan indentitas gender tertentu,” katanya.
Gender dalam Lokalitas Masyarakat Bugis
Masyarakat Bugis mengenal lima identitas gender, yaitu uruwane (laki-laki), makkunrai (perempuan), calabai (laki-laki yang menyerupai perempuan), calalai (perempuan yang menyerupai laki-laki) dan bissu (gender yang menghimpun empat gender sebelumnya).
Dalam kebudayaan Bugis Makassar, calabai dan calalai mempunyai banyak istilah. Ada salaf baine, bencong, kawe-kawe (Bukan perempuan tetapi mendekat ke gaya perempuan), dan balaki (Perempuan bergaya seperti laki-laki).
Berasarkan sejarahnya, yang menjadi bissu, meta gender menghimpun empat gender sebelummnya (uruwane, makkunrae, calabai, calalai) dominan dari calabai.
“Namun, dalam sejarah ada juga bissu yang laki-laki, ada bissu perempuan, dan ada bissu yang calalai makanya disebut meta gender karena menghimpun empat gender sebelummnya,” ucap Dr Samsurijal Ad’han.
Dalam kebudayaan Bugis, Calabai juga terbagi menjadi tiga. Ada calabai tungkena lino, pa’calabai, dan calabai kedo-kedo.
Kata Rijal, calabai tungkena lino sejak lahir memiliki sifat dan ketentuan secara alam yang tidak bisa ditolak.
“Saya telah melakukan riset berkali-kali pada komunitas bissu maupun calabai, dia menceritakan pengalamannya bahwa sejak dari kecil sudah mendapat tekanan (dari masyarakat) untuk berubah menjadi laki-laki sejati,” ucap pria kelahiran 1976 ini.
kedua, pa’calabai. Rijal mengibaratkannya sebagai pisau silet, biasa disebut abogo (bisa kanan bisa kiri).
“Pa’calabai ini sebenarnya mengidentifikasi dirinya seperti perempuan tapi bisa seperti pisau silet (laki-laki boleh dan perempuan boleh),” ucapnya.
Kalau calabai kedo-kedonami sebenarnya bukan calabai, tetapi dia berupaya bersikap calabai karena tuntutan profesi, budaya, atau menjadi gaya hidup (style).
Calabai kedo-kedonami ini dikritik oleh calabai tungkena lino karena dianggap pa’calabai. Calabai kedo-kedonami dalam mengekprsikan identitasnya juga dianggap terlalu vulgar.
Misalnya cara berpakaian seksi, calabai tungkena lino tidak sepakat dengan itu. Dalam konteks bugis, calabai tungkena lino mengekspresikan dirinya sebagai perempuan secara sopan.
“Maka calabai tungkena lino dahulu lebih banyak memakai lipa’ bate dan tidak genit. Kalo ada calabai yang ke mana-mana berpakaian seksi dan genit maka itu belum sampai calabai tungkena lino, masih termasuk pa’calabai dan calabai kedo-kedonami,” ucap Rijal.
Meskipun calabai dalam identitas gendernya merasa sebagai seorang perempuan, tetapi ketika mengekspresikan dirinya di tengah-tengah khayalak dia tahu di mana harus menempatkannya di dalam budaya yang dominan.
“Kesimpulan dari beberapa riset bahwa sebenarnya masyarakat bugis punya cara untuk mengkanalisasi orientasi seksual untuk tidak menabrak budaya dominan yang ada di masyarakat yaitu dengan menjadi bissu,” tegasnya.
Calabai yang diakui adalah calabai tungkena lino karena mereka tidak boleh mengekspresikan secara berlebihan apalagi menggunakan orientasi seksualnya.
“Mereka harus menjaga dan mengelola dengan diarahkan untuk menjadi ahli spritual atau mengabdi di kehidupan sosial dan masyarakat,” ujarnya.
Mereka adalah penyambung dalam ritual tertentu kepada yang maha kuasa kemudian ditugaskan untuk mengatur kasara (petuah) dalam masyarakat.
Penulis : Male’bi Salsabila (Magang)
Editor : Jushuatul Amriadi