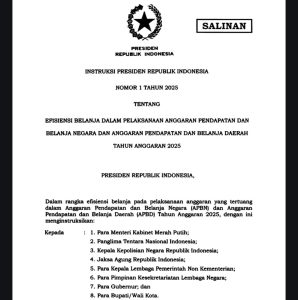Oleh : Kahlil Jaymar
Paska reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam pengeloalaan sistem Negara. Sistem yang dulunya dipakai pada masa orde baru yang sentralistik kini berubah menjadi desentralisasi yang tujuannya tak lain untuk mengedepankan sistem demokrasi di Indonesia.
Desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam pemilihan dan penetapan kepala daerahnya.
Era Desentralisasi sangat membuka ruang demokrasi selebar-lebarnya kepada rakyat dalam segala hal, termasuk dalam memilih kepala daerahnya masing-masing. Sesuai dengan regulasi Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (1) tentang pemilihan kepala daerah disebutkan bahwa “Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”
Akan tetapi apa yang dicita-citakan sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tak sesuai dengan harapan. Pilihan demokrasi liberatif malah memberikan konsekuensi hadirnya praktik bosisme lokal dalam arena pemilukada di tingkat daerah.
Bosisme lokal atau loial strongman merupakan orang kuat lokal yang lahir sebagai orang berpengaruh. Para aktor bosisme lokal seringkali berada dalam lingkaran orang partai, konglomerat, birokrat, elit lokal bahkan hingga preman sipil. Bosisme lokal dan local strongman saya menganggap statusnya sama saja karena kemampuannya dalam penguasaan resource, seperti kekayaan, kepemilikan tanah, yang pada akhirnya akan menimbulkan legitimasi pada kefigurannya.
Hadirnya para bosisme lokal di panggung pemilukada pasca reformasi telah memberikan warna tersendiri dalam proses demokratisasi yang terjadi di tingkat lokal. Kehadirannya dianggap mampu menciderai proses demokratisasi yang sedang berlangsung.
Kehadiran mereka dalam pilkada merupakan upaya untuk mengalokasi sumber daya politik dan sumber daya ekonomi daearah agar berjalan sesuai dengan alur yang mereka inginkan.
Berhasilnya para bosisme lokal yang menguasai sumber-sumber kekuasaan dan memiliki pengaruh yang besar atas jaringan masyarakat tak terlepas dari cara mereka dalam menguasai strategi politik “balas budi” yang mereka ciptakan. Kekuasaan “balas budi” yang digunakan para bosisme lokal tersebut tidak lain untuk mengontrol sumber daya politik dan sumber daya ekonomi dalam meligitimasi kekuasaanya. Dengan kata lain, Bosisme lokalah yang menguasai jalannya politik di berbagai daerah akibat lahirnya sistem desentralisasi.
Tingginya cost politik yang harus dikeluarkan oleh aktor politik juga menjadi faktor utama hadirnya penguasa lokal menjadi superior dalam proses politik di tingkat daerah. Selain itu, ditambah juga dengan tingginya pragmatisme masyarakat menjadi mudahnya jalan masuk para penguasa lokal sebagai pemilik modal untuk memainkan perannya dalam mengontrol jalannya perpolitikan di daerah.
Hasilnya para aktor politik mau tidak mau harus membuat kontrak dengan pemilik modal (penguasa lokal) yang harus dipenuhi setelah mereka mendapatkan jabatan politik tersebut.
Berbagai strategi yang juga sering dilakukan para bosisme lokal untuk memonopoli jalannya politik dan ekonomi dirtingkat daerah. Diantaranya: (1) menempatkan kerabat atau keluarga mereka untuk menduduki kursi-kursi kekuasaan ditiap daerah; (2) mengatur posisi atau penempatan pejabat daerah; (3) mengontrol proyek pemerintah dan dana aspirasi; (4) membangun mesin politik sebagai broker suara; (5) turut berperan dalam mengatur peraturan daerah; (6) mengatur pengelolaan APBD dalam pembangunan daerah; dan (7) melakukan intimidasi dan kekerasan politik.
Ada beberapa yang dapat terjadi akibat adanya praktik bosisme lokal di pilkada daerah. Seperti maraknya kasus Money Politik, Korupsi, hingga kasus premanisme jelang proses pilkada di setiap daerah. Mereka menggunakan strategi pembelian suara, manipulasi, hingga tindakan intimidasi dengan penggunaan kekerasan. Ini tentu saja telah memberikan wajah tersendiri begitu bahayanya para aktor bosisme jika memainkan perannya dalam pilkada daerah.
Selain itu, di zaman kapitalisme dan demokrasi seperti sekarang ini dimana kebutuhan ekonomi yang meningkat, ketimpangan sosial yang sangat tinggi dan kelangkaan akses terhadap kebutuhan pokok itu juga menjadi akar lahirnya pemikiran pragmatisme masyarakat sehingga membuka ruang bagi bosisme lokal untuk menjadi bos lokal.
Itulah faktor yang melatar belakangi lahirnya bosisme lokal di pemilukada daerah. Kita tentunya sangat berharap penyakit ini pulih dan kembali kepada substansi demokrasi itu sendiri.
Maka dari itu sudah seharusnya seluruh Masyarakat dan pemerintah saling bersinergi dalam membangun integritasnya di setiap proses pilkada. Sehingga, apa yg dicita-citakan oleh bangsa ini yang mengedepankan asas-asas demokrasi itu dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.
*Penulis Merupakan Mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik (FUFP) Semester III.